P.K. Ojong dan Jakob OetamaMembuka Isolasi Mencerdaskan Bangsa
Pada mulanya, keduanya adalah mantan pemimpin redaksi. Auwjong Peng Koen alias P.K. Ojong dari Star Weekly, satunya lagi Jakob Oetama dari majalah Penabur. Yang satu sangat teliti dan penuh perhitungan, yang lainnya pandai memainkan strategi pengaturan sumber daya manusia. Mereka bergabung menjadi kekuatan yang tak bisa dibendung oleh zaman."The Dynamic Duo". Itulah P.K. Ojong dan Jakob Oetama. Pada awal 1960-an, Ojong dan Jakob sering bertemu dalam gerakan asimilasi. Mereka juga duduk dalam kepengurusan Ikatan Sarjana Katolik Indonesia. Jakob Oetama sebagai ketua dan Ojong sebagai bendahara.Keduanya selalu nyambung ketika berbicara. Mereka sepakat bahwa pembaca Indonesia pada waktu itu terkucil. Sebab tak ada majalah luar negeri yang diperbolehkan masuk ke negeri ini. Mareka berencana membuat majalah untuk menerobos isolasi pemerintah. Keduanya sepakat untuk jauh dari persoalan politik. Majalah yang akan diterbitkan berisi tentang perikehidupan manusia yang nyata, kongkret, bukan renungan abstrak.Ojong dan Jakob beruntung karena percetakan PT Kinta menyediakan fasilitas yang mereka butuhkan. Majalah baru itu diberi bekas ruangan redaksi Star Weekly. Sebagai sumber tulisan, mereka menggunakan majalah dan koran dari luar negeri. Ini mereka dapatkan dari kedutaan-kedutaan yang ada di Jakarta.Ketika itu, hubungan P.K. Ojong dengan pihak kedutaan sudah terjalin erat. Ojong dan Jakob juga mengontak sejumlah orang untuk menulis di majalah tersebut. Misalnya Widjojo Nitisastro, Sanjoto Sastromihardjo, Nugroho Notosusanto, dan Tan Fay Tjhion. Untuk menerbitkan majalah tadi, keduanya kemudian membentuk sebuah yayasan.Ini sejalan dengan anjuran pemerintah, yang lebih suka format yayasan ketimbang perseroan terbatas. Kemudian terbentuklah Yayasan Intisari. Untuk mendapatkan izin terbit, mereka pergi ke gedung Kodam Jaya di Jalan Perwira, Jakarta. Intisari, begitu nama majalah tersebut, terbit perdana pada 17 Agustus 1963. Nama Jakob Oetama tercantum sebagai pemimpin redaksi, sedangkan P.K. Ojong dan Josephus Adisubrata sebagai pengasuh.Format majalah itu kecil, dengan dimensi 14 x 17,5 cm dan tebal 128 halaman. Tak ada kulit muka di awal terbitnya majalah bulanan tersebut. Begitupun, 10.000 eksemplar edisi perdana majalah itu habis terjual (dengan harga Rp 60 untuk Jakarta dan Rp 65 untuk luar Jakarta). Melihat prestasi penjualan itu, Ojong dan Jakob kemudian menambah jumlahnya menjadi 12.000 eksemplar pada edisi kedua.Sayang, majalah itu hanya laku 11.000 eksemplar. Kiprah Ojong dan Jakob tak berhenti di Intisari. Sebuah ide dilontarkan Jenderal A. Yani kepada Frans Seda agar kalangan Katolik memiliki sebuah koran untuk mengimbangi sepak terjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) dan kawan-kawannya. Ide ini sempat tidak bisa diwujudkan kalau saja Seda tidak bertemu dengan P.K. Ojong dan Jakob Oetama.Dibentuklah yayasan bernama Bentara Rakyat. Selanjutnya izin terbit diurus. Meski menurut Frans Seda yayasan itu sudah mendapat restu dari Bung Karno, masih dipersulit juga perizinannya. Maklum, aparat yang mengurus izin terbit dikuasai PKI. Satu syarat yang mustahil dipenuhi pada saat itu ialah jumlah pelanggan minimal sebanyak 3.000 orang.Frans Seda tak kurang akal. Ia mengerahkan banyak orang Flores sehingga persyaratan oplah minimal itu dapat terpenuhi. Aparat tak bisa berdalih lain kecuali memberi izin ketika yayasan itu mengajukan 3.000 nama, lengkap dengan alamat dan tanda tangan. Seda kemudian melaporkan semua itu kepada Bung Karno.Presiden pertama RI itu lalu menanyakan nama koran yang bakal diterbitkan Seda. Bung Karno malah memberi nama, yang kemudian abadi hingga sekarang: Kompas. Ketika nama itu disodorkan kepada para pengurus yayasan, tak ada yang keberatan sama sekali. Dengan modal awal Rp 100.000 --sebagian merupakan uang Intisari-- pada 28 Juni 1965 Kompas nomor percobaan terbit perdana.Edisi percobaan ini dicetak selama tiga hari berturut-turut, sebelum akhirnya terbit Kompas sesungguhnya. Di awal kemunculannya, harian ini kerap datang terlambat sehingga pernah dijuluki "Komt pas morgen": besok baru datang. Ini terjadi karena Kompas belum memiliki percetakan. Karena koran baru, Kompas selalu harus mengalah pada media yang ada lebih dulu ketika di percetakan.Kondisinya berubah setelah peristiwa G-30-S. Kompas menggantikan posisi harian Suluh Indonesia, yang dilarang terbit, di percetakan PT Kinta. Pasca-peristiwa G-30-S, banyak koran yang gulung tikar. Ini menciptakan peluang bagi Kompas. Koran ini pun banyak dilirik orang.Lalu, meski banyak koran yang sudah mapan terbit kembali, Kompas tetap dicari banyak orang. Pada 1968, tiras Kompas melampaui Sinar Harapan dan duduk di peringkat kedua, di bawah harian Berita Yudha. Hasil audit SGV Utomo pada 1969 menyebutkan, tiras Kompas melewati koran-koran lain di Indonesia.Popularitas dan tiras tinggi koran muda ini sesungguhnya bukan tujuan utama Ojong ketika mendirikan Kompas. "Biar orang lain saja yang tirasnya paling tinggi," katanya. Sesungguhnya ia lebih mendambakan koran macam Milwaukee Journal, koran lokal di Amerika Serikat, yang tirasnya hanya beberapa puluh ribu eksemplar.Koran tersebut beken karena wartawannya bebas dari hubungan akrab dengan penguasa. Hubungan macam itu, kata Ojong, bisa membatasi kebebasan wartawan dalam melakukan kritik. Selain hubungan dengan narasumber itu, Ojong juga menerapkan disiplin tinggi kepada pegawai Kompas. Ia memberi contoh dengan cara datang di kantor pukul tujuh pagi.Hal itu membuat para pegawai lainnya malu untuk datang terlambat. Kepada pegawai di bagian percetakan, Ojong juga kerap memberi gambaran pentingnya disiplin. Ia sering mengaitkan disiplin waktu dengan kerugian yang mungkin timbul. Inilah yang kemudian menjadi salah satu kunci sukses Kompas, hingga mampu bertahan selama empat dekade lebih.Diversifikasi usaha dalam tubuh Kompas bukan semata-mata urusan bisnis. Namun, seperti dikatakan Ojong, itu adalah cara perusahaan mengembalikan keuntungan kepada karyawannya. "Karyawan menginvestasikan hidupnya pada perusahaan. Jadi, perusahaan juga harus memikirkan jaminan masa tua mereka," ujarnya, seperti ditulis Helen Ishwara dalam buku P.K. Ojong: Hidup Sederhana, Berpikir Sederhana.Kalau keuntungan satu perusahaan dibagi-bagikan begitu saja dalam bentuk uang, ia akan habis dikonsumsi. Namun, bila keuntungan itu dipakai membuka lapangan kerja baru, ia akan bisa menghidupi banyak orang. Lagi pula, kerja memberi harga diri pada manusia. Lebih baik memberi pancing daripada memberi ikan. Begitu Ojong membeberkan dasar pikirannya.Karena itu, pada 1970, Ojong mendirikan Toko Buku Gramedia. Semula, Ojong hanya ingin menjual buku-buku paperbacks. Belakangan, toko itu adalah perpanjangan tangan bisnis penerbitannya, yakni Gramedia. Pada 1974, penerbit Gramedia menerbitkan buku pertamanya, yakni novel Karmila karya Marga T., yang sebelumnya cerita bersambung di Kompas.Toko Buku Gramedia baru ada enam (tiga di Jakarta dan masing-masing satu di Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya) ketika Ojong dipanggil Yang Mahakuasa pada 1980. Kini Toko Buku Gramedia tersebar merata di berbagai kota besar Tanah Air dan menjadi salah satu rujukan toko buku bagi masyarakat Indonesia.Dengan oplah yang makin meningkat, tentu memiliki percetakan sendiri menjadi keharusan. Inilah yang kemudian mendorong Ojong dan Jakob mendirikan percetakan sendiri. Pada 1971, proyek pembangunan percetakan ini dimulai di kawasan Palmerah Selatan, Jakarta. Pada Agustus 1972, percetakan itu mulai berfungsi. Tiga bulan kemudian, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikannya.Pada 1972, Ojong mendirikan stasiun radio komersial Sonora. Anak perusahaan ini berlokasi di Jalan Gajah Mada, Jakarta. Hingga kini, radio Sonora masih mengudara, dengan kekhasan suara penyiar, program acara abadi macam :Anda Meminta Kami Memutar", dan jingle ansambel gitar yang sudah berpuluh tahun diudarakan Sonora.Setahun kemudian, majalah anak-anak Bobo lahir, lalu disusul oleh majalah remaja Hai, yang terbit pada 1977. Keduanya adalah pengembangan dari rubrik anak-anak dan remaja yang ada di Kompas. Pada 1976, sempat didirikan Gramedia Film. Perusahaan ini menghasilkan film Suci Sang Primadona dan sempat diganjar Piala Citra. Hanya saja, perusahaan ini tidak berumur panjang.Ojong dan Jakob juga mulai merintis bisnis perhotelan, dengan membeli hotel-hotel kecil di Bandung, Semarang, dan Bali. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal jaringan Hotel Santika.Ketika pada 1978 Kompas mengalami pembredelan, unit usaha yang telah didirikan itu menjadi salah satu jalan keluar untuk menampung sementara karyawannya. Setelah pembredelan itu pula, Ojong dan Jakob makin serius membenahi dan mengelola unit usaha di luar bisnis inti Kompas-Gramedia tadi. Keduanya khawatir, pembredelan berikutnya dialami Kompas.Namun tidak semua unit usaha yang dikembangkan Ojong dan Jakob sukses. Sebelum ada Hai, sempat pula lahir majalah remaja bernama Midi. Sayang, majalah ini kurang sukses sehingga penerbitannya dihentikan. Bisnis pabrik oksigen juga mengalami kegagalan. Di luar kegagalan minor itu, Kompas-Gramedia tumbuh menjadi gurita penerbitan.Sayang, Petrus Kanisius Ojong tak bisa melihat kelanjutan usaha yang dibinanya. Ia meninggal pada 31 Mei 1980. Namun warisan pemikiran dan disiplinnya tetap dipertahankan oleh Jakob Oetama dan terlihat hingga kini.Haji Masagung dan B.M. DiahDua tokoh penting lainnya dalam bidang penerbitan dan percetakan ialah Haji Masagung dan B.M. Diah. Terlahir dengan nama Tjio Wie Tay, Masagung mulai mengembangkan naluri bisnis penjualan buku sejak 1948 lewat kongsi dagangnya dengan The Kie Hoat Lie dan Thay San (yang terakhir ini kemudian mengundurkan diri). Kongsi itu lalu dikembangkan menjadi firma bernama NV Gunung Agung (yang diambil dari makna namanya).Pada 8 September 1953, pria kelahiran Jakarta, 8 Oktober 1927, itu menggelar pameran buku. Dengan modal Rp 500.000, dipamerkanlah sekitar 10.000 buku. Momen inilah yang dicanangkannya sebagai hari lahir Gunung Agung. Kiprah Masagung dengan Gunung Agungnya ketika itu menarik perhatian banyak kalangan. Tahun berikutnya, Masagung dan kawan-kawan mengadakan Pameran Buku Indonesia. Dalam ajang inilah ia bertemu dan berkenalan dengan dwitunggal pemimpin Indonesia yang sangat dikaguminya: Bung Karno dan Bung Hatta.Pameran buku kemudian menjadi tradisi Gunung Agung dan sempat diadakan di Singapura dan Malaysia. Seiring dengan perkembangannya, Gunung Agung membuka cabang di berbagai kota, seperti Yogyakarta, Medan, Riau, hingga Irian Barat. Pada 1965, ia membuka cabang di Tokyo, lalu Singapura. Pada 1963, Gunung Agung memiliki gedung baru di Jalan Kwitang 6, Jakarta. Jenis usaha yang dirambahnya pun tak lagi sebatas menjual buku.Masagung mengembangkan penerbitan, distribusi, dan percetakan. Penerbitan di bawah nama PT Gunung Agung boleh dibilang mencapai puncaknya pada 1960-an dan 1970-an. Sayap bisnisnya pada tahun-tahun itu kian lebar lewat kerja sama dengan perusahaan lain. Dengan Sarinah, misalnya, ia membangun duty free shop lewat PT Sari Agung. Gunung Agung menjadi distributor terkemuka untuk alat-alat tulis dan perkantoran, juga buku dan majalah asing. Masagung pun kemudian menekuni bisnis money changer lewat PT Ayumas. Perdagangan komputer dan perhotelan tak pula lepas dari jangkauannya.Namun, agaknya, Masagung sangat menyadari bahwa usianya terbatas, sedangkan usahanya harus terus berjalan. Pada 1980-an, pelan-pelan ia mengalihkan bidang usaha ini kepada putra-putranya. Peralihan bisnis keluarga dari generasi pertama ke generasi kedua ini boleh dibilang berjalan mulus. Tiada terdengar perebutan kekuasan di antara ketiga putranya: Putra Masagung, Oka Masagung, dan Ketut Masagung. Pengelolaan Gunung Agung kepada kaum profesional dilakukan pada 1989. Dua tahun kemudian, perusahaan yang kini bernama PT Toko Gunung Agung ini mencatatkan diri di Bursa Efek Jakarta.Burhanuddin Mohamad (B.M.) Diah belajar di HIS, kemudian melanjutkan ke Taman Siswa di Medan. Ia pindah karena tak mau belajar di bawah asuhan guru-guru Belanda. Ketika berusia 17 tahun, B.M. Diah berangkat ke Jakarta dan menuntut ilmu di Ksatriaan Instituut, pimpinan Dr. E.E. Douwes Dekker. Ia memilih jurusan jurnalistik dan banyak belajar dari Dekker.Setelah tamat, B.M. Diah kembali ke Medan dan menjadi redaktur harian Sinar Deli. Setengah tahun kemudian, ia kembali ke Jakarta dan bekerja di harian Sin Po. Tak lama kemudian, ia pindah ke Warta Harian. Di koran ini, B.M. Diah hanya bekerja tujuh bulan sebelum koran itu dibubarkan pemerintah. B.M. Diah lalu mendirikan media sendiri, Pertjatoeran Doenia, yang terbit bulanan.Di era kekuasaan Jepang, B.M. Diah bekerja rangkap di radio Hosokyoku sebagai penyiar siaran bahasa Inggri, dan di harian Asia Raja. Meski sempat mendekam empat hari di penjara karena ketahuan kerja rangkap, lewat radio Hosokyoku ia bertemu dengan Herawati, yang kemudian dinikahinya pada 18 Agustus 1942. Bung Karno dan Bung Hatta hadir dalam pernikahan itu.Pada akhir September 1945, setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia diumumkan, B.M. Diah bersama sejumlah rekannya, seperti Joesoef Isak dan Rosihan Anwar, mengangkat senjata dan berusaha merebut percetakan Djawa Shimbun, yang menerbitkan harian Asia Raja. Meskipun Jepang telah menyerah kalah, teman-teman B.M. Diah ragu-ragu, mengingat mereka masih memegang senjata. Kenyataannya, tentara Jepang yang menjaga percetakan menyerah. Percetakan pun jatuh ke tangan B.M. Diah dan rekan-rekannya.Pada 1 Oktober 1945, B.M. Diah mendirikan harian Merdeka. Ia menjadi pemimpin redaksi, Joesoef Isak menjadi wakilnya, dan Rosihan Anwar menjadi redaktur. Belakangan, Joesoef Isak terpaksa diberhentikan atas desakan pemerintahan Orde Baru. Rosihan Anwar juga keluar dan mendirikan harian Pedoman. B.M. Diah memimpin surat kabar itu hingga akhir hayatnya, meskipun belakangan ia lebih banyak menangani PT Masa Merdeka, penerbit harian Merdeka. Pada April 1945, bersama istrinya, Herawati, B.M. Diah mendirikan koran berbahasa Inggris, Indonesian Observer.Pada 1959, B.M. Diah diangkat menjadi Duta Besar RI untuk Cekoslowakia dan Hongaria. Lalu berlanjut mengisi posisi yang sama di Inggris dan Thailand. Pada 1968, ia diangkat Presiden Soeharto menjadi Menteri Penerangan. Belakangan, B.M. Diah diangkat menjadi anggota DPR, lalu anggota DPA. Di usia tuanya, B.M. Diah mendirikan Hotel Hyatt Aryaduta (di lahan rumah orangtua Herawati).Karena perjuangan dan jasa-jasanya bagi negara, B.M. Diah dianugerahi Bintang Mahaputra Utama (dari Presiden Soeharto, 10 Mei 1978) serta piagam penghargaan dan Medali Perjuangan Angkatan '45 (dari Dewan Harian Nasional Angkatan '45, 17 Agustus 1995). B.M. Diah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Sumber (Klik : gatra.com)





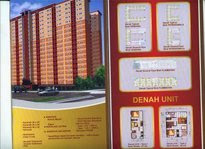
0 comments:
Post a Comment