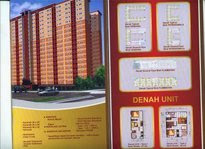ANDA sudah pernah keliling-keliling Bandara Changi? Kalau belum, saya sarankan kalau kebetulan Anda pergi ke Singapura, coba luangkan waktu untuk jalan-jalan di situ. Bandara Changi ini buat saya bukan sekadar bandara, namun lebih mirip sebuah kawasan wisata.Dari dalam kota Singapura, ke bandara ini paling enak naik mass rapid transit (MRT). Murah, cepat, dan nyaman. Lalu, begitu sampai di stasiun MRT Changi, Anda tinggal naik eskalator yang cukup tinggi ke Terminal 2 (T2). Nah, penjelajahan Anda bisa dimulai. Dari sini Anda bisa keliling-keliling T2, Terminal 1 (T1) atau Terminal 3 (T3).
Baiklah, kita ke T3 yang umurnya belum segenap setahun. T3 ini dibuka pada 9 Januari 2008 yang ditandai dengan kedatangan pesawat Singapore Airlines dari San Francisco, Amerika. Dari T2 atau T1, Anda bisa menuju ke T3 ini dengan menggunakan Skytrain yang beroperasi dari jam 5 pagi sampai jam setengah tiga dini hari.
Nah, bangunan T3 ini secara keseluruhan nampak jauh lebih luas ketimbang T1 dan T2. Arsitekturnya bersifat “open concept”. Hampir seluruh dinding dan atapnya terbuat dari kaca yang tembus pandang, sehingga memudahkan orang untuk melihat pesawat Airbus A380 yang baru. T3 ini memang dipersiapkan untuk menyambut pesawat superjumbo yang berkapasitas besar itu. Dengan adanya T3 ini, kapasitas penumpang maksimum yang bisa dilayani Bandara Changi akan bertambah sebanyak 22 juta orang. Ditambah T1 dan T2, Bandara Changi secara total mampu melayani 70 juta penumpang setiap tahunnya.
Jumlah ini jauh di atas angka penumpang pada tahun 2007 yang sebesar 36,7 juta penumpang. Namun, pengelola Bandara Changi, Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS), memang punya kebijakan untuk selalu melihat jauh ke depan. Diharapkan tidak akan terjadi penumpukan penumpang (congestion) atau menurunnya layanan karena kapasitas bandara yang tidak memadai lagi nantinya.
Nah, selepas dari pintu Skytrain tadi, di sebelah kiri, persis berdempetan dengan T3 ini, ada Hotel Crowne Plaza yang eksterior dan interiornya cukup artistik. Di sebelah kanan juga bisa kita lihat yang disebut Green Wall, yaitu dinding setinggi lima meter yang dihiasi dengan 25 spesies tanaman yang menjulur dari atas ke bawah. Ada juga air terjun sehingga kesan tropis sangat terasa di sini. Atapnya sendiri didesain sedemikian rupa sehingga penerangannya bisa alami. Di langit-langitnya ada semacam bilah-bilah papan metalik yang bergelantungan. Rupanya ini untuk membantu menjaga temperatur dan kelembaban dengan menggunakan tenaga listrik seefisien mungkin.
Di dalam T3 ini sendiri banyak aktivitas yang bisa kita kerjakan. Kalau lapar, Anda bisa mencari makanan di food court alias Kopi Tiam yang areanya cukup luas dengan kedai makanan yang sangat variatif. Di sini Anda bisa makan roti kaya di Ya Kun Kaya Toast misalnya, sambil berselancar Internet karena seluruh area T3 ini sudah dilengkapi fasilitas Wi-Fi.
Buat ibu-ibu yang ingin dandan, di sini juga ada kamar hias untuk wanita yang terpisah dari kamar kecil, lengkap dengan meja hiasnya. Letaknya di area keberangkatan (departure). Kalau mau berbelanja, ada supermarket FairPrice NTUC yang beroperasi dari jam 7 pagi sampai 11 malam. Bahkan, kalau mau menonton film, di sini juga ada bioskop yang buka 24 jam dan gratis untuk penumpang atau calon penumpang pesawat.
Sebenarnya fasilitas yang ada di T1 dan T2 juga tidak kalah dengan di T3 ini. Di kedua terminal yang masing-masing diresmikan pada tahun 1981 dan tahun 1991 ini, ada sejumlah fasilitas yang sangat memanjakan penumpang, calon penumpang, atau pengunjung yang sekadar ingin jalan-jalan.
Ada lebih dari 100 gerai ritel, termasuk gerai merek-merek ternama seperti Prada, Gucci, Bulgari, Hermès, FIFA Official Store, dan toko ritel travel Ferrari. Ada Viewing Hall, yang kadang dikunjungi oleh sekelompok anak muda untuk melukis pesawat yang lalu-lalang di bandara. Ada pula business centre, tempat ibadah, gym, area tidur 24 jam, tempat bermain anak, enam taman terbuka, lounge dengan fasilitas shower dan spa, kolam renang, dan masih banyak lagi. Pokoknya serba komplit.
Sangat menarik, bukan? Seperti saya bilang, ini lebih mirip kawasan wisata. Bandara Changi ini bukan sekadar terminal tempat transit atau singgah semata, tapi juga sudah jadi tempat tujuan akhir (destination). Nah, inilah contoh Caring di era New Wave Marketing.
CAAS sebagai pengelola Bandara Changi benar-benar memperhatikan setiap orang yang berkunjung ke situ. Mereka diperlakukan sebagai manusia yang punya kebutuhan dan interest spesifik, bukan sebagai penumpang atau calon penumpang saja yang hanya membutuhkan layanan penerbangan. Caring yang beyond service seperti inilah yang harus dilakukan oleh para New Wave Marketers.
-- Ringkasan tulisan ini bisa dibaca di Harian Kompas --
Hermawan Kartajaya
(www.kompas.com)
Selanjutnya.....
Selanjutnya...